"Nina bobo, oh Nina bobo ...
kalau tidak bobo ...." Nyanyian kuhentikan. Damai wajah bocah kecil itu pulas
tertidur berbantalkan lenganku yang kekar.
"Bapak, sayang Nina,"
bisikku.
Enam tahun sudah usianya kini.
Gadis kecilku sudah bisa melakukan begitu banyak hal sendiri. Rasanya baru
kemarin kutimang-timang ia dengan kedua tangan. Mengganti popoknya, memastikan
susu yang akan diminumnya bersuhu pas, tidak dingin, tidak juga terlalu panas.
Dalam usianya kini, semakin
pintar ia bertanya tentang banyak hal. Tentang bagaimana cara burung terbang,
tentang ke mana perginya matahari saat malam. Termasuk pertanyaan yang selalu
bisa membuat lidahku kelu. Bukan sebab tak tahu jawabannya, tetapi karena aku
tak punya nyali untuk menjawab.
"Pak, ibu Nina di mana? Kata
teman-teman Nina nggak punya Ibu, ya?" Polos wajahnya bertanya.
Kuangkat tubuh mungilnya ke atas
pangkuan. "Setiap orang, itu lahir dari seorang ibu, Nak. Jadi nggak ada
yang nggak punya ibu."
"Ibu Nina di mana,
Pak?"
"Kan udah ada Bapak. Bapak
juga bisa jadi ibu."
"Ih, Bapak. Ibunya teman
Nina itu pakai kerudung. Bapak, nggak pakai kerudung," protesnya.
"Eh, Bapak juga bisa tahu.
Begini, ‘kan?” Kukerudungkan kain panjang yang biasa dipakai untuk menggendongnya
dulu. “Ih, cantikan juga Bapak!"
Nina tertawa. Ah, tawa renyah itu
adalah semangat hidupku.
Aku tak akan pernah lupa saat
bibir mungilnya pertama kali berucap "Papa" dengan terbata-bata. Sampai
pada akhirnya ia mampu memanggilku bapak dengan sempurna. Rasanya seperti
seluruh dunia berada di genggamanku saat itu.
"Hah, anakku nyebut aku bapak. Kalian semuanya dengar? Dia udah bisa
memanggilku bapak!" sorakku pada seluruh tetangga. Mereka pun turut
gembira.
Apa semua orang tua akan
merasakan hal yang sama? Hidupku berubah, hadirnya bak semburat fajar dalam
gelap dan gigilnya waktu subuh. Segala sesuatu menjadi lebih berarti, seluruh
hidupku memiliki satu tujuan yang pasti.
Belum banyak hal mampu kupersembahkan
untuk bidadari kecil itu. Sekadar boneka yang ia mau saja, lama aku harus
menyisihkan upahku sebagai buruh bangunan, mengumpulkan recehan sisa kami
makan.
Sungguh seluruh lelahku luruh, saat
tiba di rumah senyum manisnya yang menyambut.
"Bapak pulang! Bapak pulang!
Bapak pulang!" Ia berlari sambil terus memanggil-manggil namaku. Nina merentangkan
tangan, pertanda wajib atasku segera menggendongnya. Kalau tidak, tuan putriku
akan merajuk.
"Ibu ...," gumamnya di
dalam lelap.
Hatiku perih bukan kepalang. Betapa
aku menyadari tidak akan pernah bisa hadir sebagai ayah dan ibu dalam waktu
bersamaan. Kerinduan yang luar biasa memenuhi benaknya, pasti.
Apa yang bisa kukatakan padanya.
Aku tak ingin Nina berhenti memanggilku bapak, jika ia tahu yang sebenarnya bahwa
dirinya bukanlah darah dagingku. Aku pun tak memiliki seorang istri yang bisa ia
anggap sebagai ibu. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai, pada akhirnya
memilih untuk pergi saat menyadari dia punya pilihan untuk hidup lebih baik.
Bagaimana aku bisa menceritakan seperti
apa wajah ibunya. Haruskah kukatakan, pada malam itu aku menemukannya di dalam
sebuah kardus. Lalu bagaimana jika selanjutnya anak pintar itu kembali
bertanya, apa kardus itu adalah ibunya.
Jika memang begitu, maka kami
memiliki ibu yang sama. Sebab kata mereka yang merawat dan membesarkanku dulu,
aku pun ditemukan di dalam sebuah kardus, saat bahkan tali pusatku masih basah
dan tubuh merahku berlumuran darah.
Seperti apa wajah ibu kita, Nak?
Aku pun rindu. Tak pernah sekali pun aku merasakan hangat dekapnya, sentuh kasihnya,
atau bahkan berisik omelannya.
Siapa ibu kita, Nak.
Cirebon, 20 Juli 2019.

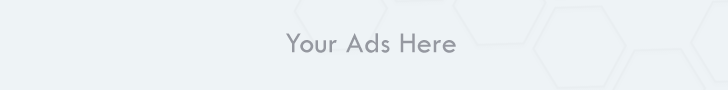








EmoticonEmoticon